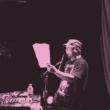Malam itu udara Kudus terasa sakral. Di halaman Monumen Kretek Indonesia tanggal 3 Oktober lalu obor-obor menyala seperti bintang yang jatuh ke bumi, menyalakan ruang antara ritual dan ingatan. Saya berdiri di antara kerumunan, menghirup aroma cengkih dan tembakau yang terbawa angin. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar upacara; seolah kita sedang memanggil kembali ruh yang lama tertidur—ruh dari tanah, tangan, dan sejarah yang bernama kretek.
Teater Djarum menamai pertunjukan malam itu Puja Doa Kretek. Mereka berbaris melingkar, mengenakan kain putih dan selendang kotak hitam-putih di pinggang. Gerak mereka pelan, nyaris seperti doa. Di tengah lingkaran, seorang perempuan menunduk membawa wadah berisi campuran rempah, sementara obor-obor diangkat tinggi ke langit. Api berpendar di wajah para pelaku ritual; tiap nyala seperti jiwa yang berbicara. Tidak ada kata, hanya desah napas, denting bambu, dan bunyi daun kering yang terinjak pelan.
Saya merasakan sesuatu yang menegangkan di dada—sebuah kesadaran yang muncul diam-diam: bahwa di balik setiap kepulan asap kretek, tersembunyi lapisan-lapisan sejarah sosial yang belum benar-benar dipahami.
Bahwa kretek bukan semata industri atau kebanggaan ekonomi, melainkan kisah manusia yang menegosiasikan nasib, keyakinan, dan identitas mereka di bawah langit Kudus.
Dalam teori identifikasi sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Henri Tajfel, manusia selalu membentuk rasa “kita” dan “mereka”. Malam itu saya menyaksikan bagaimana Puja Doa Kretek menjadi ruang “kita” bagi masyarakat Kudus: petani, perajin, seniman, dan warga yang merasa hidup mereka terikat oleh aroma tembakau dan cengkih.
Namun saya juga sadar, bahwa “kita” ini masih berhadapan dengan “mereka” — para penggagas, lembaga, atau bahkan pemerintah yang berupaya menetapkan Hari Kretek Nasional tanpa benar-benar menelusuri denyut asalnya. Ada jarak antara simbol dan akar, antara deklarasi dan ziarah.
Kretek, yang lahir dari tangan Djamhari di Kudus Kulon, tumbuh dalam ruang budaya yang khas: tempat agama, tradisi, dan ekonomi berbaur dalam satu tarikan napas. Kudus Kulon adalah situs yang hidup, bukan sekadar catatan sejarah. Namun anehnya, hari kretek justru ditentukan dari tanggal peresmian museum dan deklarasi komunitas, seolah asal-muasal yang sejati bisa diganti dengan momentum simbolik.

Sebagai penulis yang menyaksikan langsung Puja Doa Kretek, saya merasakan bahwa ritual itu bukan perayaan, melainkan peringatan—peringatan agar kita tak gegabah menamai sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya.
Kretek Sebagai Filsafat Sosial
Kyai H. Aslim Akmal malam itu mengingatkan, kretek pernah menjadi bagian dari laku spiritual masyarakat Kudus. Di pesantren, sebatang kretek diletakkan dalam sesajen, bukan untuk disembah, tetapi untuk dihormati sebagai simbol hubungan antara manusia, bumi, dan leluhur. Dalam pandangan filsafat sosial, hal ini menunjukkan bahwa kretek telah menjadi praksis budaya—perwujudan kesadaran sosial yang menembus batas ekonomi dan ritual.
Maurice Merleau-Ponty mungkin akan menyebutnya sebagai pengalaman yang berinkarnasi—sebuah makna yang melekat pada tubuh, pada tindakan, bukan pada konsep. Sementara Karl Marx, dalam konteks berbeda, akan melihatnya sebagai bentuk kesadaran kelas: hasil dari kerja tangan-tangan yang menumbuk rempah, melinting tembakau, dan menjaga bara kehidupan dari balik asap.
Dengan begitu, kretek bukan hanya produk; ia adalah bentuk pengetahuan tubuh, hasil dari dialog panjang antara manusia dan alam.
Setiap tarikan kretek adalah tarikan terhadap sejarah itu sendiri.
Barangkali, pemerintah belum menetapkan Hari Kretek karena para penggagasnya belum benar-benar menziarahi sumbernya. Belum ada riset mendalam di Kudus Kulon, tempat mula bara pertama dinyalakan. Para pegiat hari kretek sibuk merayakan, namun belum sungguh-sungguh menggali: siapa Djamhari dalam lanskap sosialnya, bagaimana relasi antara kretek dan pesantren, antara ritual dan kerja harian para buruh linting?
Hari Kretek mestinya tidak ditentukan hanya dari tanggal peresmian museum atau deklarasi komunitas. Ia seharusnya lahir dari pemahaman mendalam, dari pertemuan antara sejarah dan kesadaran. Sebab menetapkan hari berarti juga menegaskan makna, dan makna tanpa akar hanyalah seremonial kosong.

Ketika Puja Doa Kretek usai, para peserta berjalan mengelilingi Monumen Kretek dalam hening total. Langkah-langkah mereka tanpa alas kaki menyentuh tanah yang sama dengan tanah yang pernah diinjak Djamhari. Saya berdiri diam, menyadari bahwa malam itu bukan sekadar peringatan, tetapi perenungan.
Dalam keheningan itu, saya belajar satu hal: bahwa sebelum kita menetapkan Hari Kretek, kita harus lebih dulu menyalakan bara ingatan. Menemukan kembali akar yang hilang, menelusuri jejak Kudus Kulon dengan rendah hati, dan memaknai kretek bukan hanya sebagai komoditas, tapi sebagai narasi sosial yang membentuk jati diri bangsa.
Sebab, seperti bara yang masih berpijar di ujung malam, sejarah kretek belum padam—ia hanya menunggu orang-orang yang mau meniupnya dengan kesadaran, bukan hanya dengan seremoni.
Editor: Arlingga Hari Nugroho
Foto sampul: Imam Khanafi