Yang paling nyata dari Biennale Jogja 18 (BJ18) bagi saya bukanlah wacananya, melainkan tubuh: tubuh seniman, tubuh pekerja, tubuh karya yang tersandung oleh proses produksi yang rapuh. Maka ketika saya membaca dua teks—Kesulitan Mencari Makna di Biennale Jogja 18 karya Ibrahim Soetomo dan Mudahnya Mencari Makna di Biennale Jogja 18 karya Darryl Haryanto—saya membacanya bukan dari kursi penonton, melainkan dari lantai pameran yang masih berdebu.
Apa yang mereka perdebatkan tidak hadir sebagai diskursus kosong, melainkan sebagai situasi yang telah saya jalani sendiri: kerja yang terputus-putus, keputusan yang limbung, dan infrastruktur yang tak pernah benar-benar siap.
Saya bagian dari Situationist Under-Record (SUR), proyek yang diundang BJ18. Tulisan ini hanyalah curhat colongan—bukan mewakili SUR, melainkan suara personal saya di tengah riuh diskursus.
Karya SUR sejak awal dirancang sebagai proyek site-specific di Ndalem Brotoasmaran (Ndalem): soundwalk, partisipasi warga, rute tubuh, pertemuan cerita mistis dengan polemik politik lokal—semuanya terikat pada satu tempat konkret. Kami juga meminta sebuah ruang gelap untuk presentasi tambahan, yang kami bayangkan sebagai dessert atau appetizer: kudapan pembuka atau penutup menuju pengalaman utama di Ndalem.
Yang terjadi justru di luar nuril—meski, mungkin, masih di dalam kebiasaan. Karena MoU dengan keluarga pemilik Ndalem tak kunjung selesai, presentasi utama di Ndalem batal total. Yang tersisa hanyalah bagian pembuka/penutup yang berdiri sendiri—lepas dari konteks sosial-politik Ndalem yang seharusnya menjadi tubuh karya.
Keterputusan itu makin kentara ketika ruang gelap tersebut akhirnya berdiri di Monumen Bibis—sebuah lokasi dengan sejarah dan beban politiknya sendiri. Rencana relasional runtuh menjadi pecahan presentasi yang gagal membaca konteks Monumen Bibis sebagai lokasi pamer. Proyek yang semula merajut ruang, tubuh, suara, dan warga berubah menjadi fragmen-fragmen yang tak lagi saling bicara.

Ketika membaca kritik Ibrahim tentang ketiadaan “tubuh kawruh” di level presentasi—bahwa karya SUR menjadi “salah ruang” dan “salah kuratorial”—saya merasa itu tepat sasaran. Ia berbicara melampaui soal kerapian teknis: ia menunjuk kegagalan pameran menjalankan fungsi dasarnya sebagai medium komunikasi publik.
Riset panjang, kerja kolaboratif dengan warga, dan muatan sosial yang berat tak menjelma menjadi pengalaman yang dapat dipahami pengunjung. Yang banyak muncul justru kebingungan. Bukan perjumpaan, apalagi penubuhan pengetahuan.
Namun membaca tulisan Darryl, saya juga merasa ia benar dari sisi lain. Kekacauan presentasi berakar pada proses produksi yang rapuh: pekerja lapangan terlampau lelah, izin tak pasti, jadwal terus bergeser, serta koordinasi yang tersendat oleh pengambilan keputusan yang terlampau terpusat namun lamban dieksekusi.

Hari Selasa, 7 Oktober bagi saya merangkum situasi itu dengan telak.
Saat sebuah tur pameran, entah resmi program BJ18 atau bukan, berlangsung di ruang seberang, saya dan kawan-kawan SUR masih memotong, mengecat, dan memasang triplek untuk menyelesaikan partisi ruang kami. Sejak awal kami meminta ruang gelap sempurna—kontrol visual mutlak bagi karya bunyi kami di sini. Namun pameran sudah berjalan ketika ruang itu bahkan belum siap. Rombongan tur hampir masuk ke ruang kami; mungkin kami yang masih bekerja dikira bagian dari karya. Kontemporer sekali.
Pada hari yang sama kami baru mendapatkan speaker stereo yang kami butuhkan. Sebelumnya, sistem suara yang terpasang hanya mono. Padahal dalam rancangan karya—yang terpaksa kami rombak secara tergesa sebagai antisipasi batalnya presentasi di Ndalem—pemisahan kanal merupakan elemen kunci.
Pergantian speaker baru terjadi setelah Bob Edrian, salah satu kurator, diyakinkan Yossy Herman bahwa output dari speaker lama sekadar “dual mono”—absurd. Speaker pengganti pun bukan dari inventaris yang tersedia, melainkan diambil dari ruang seniman lain di Monumen Bibis.
Belakangan baru disadari oleh seniman yang speaker-nya kami ambil: suara di ruangannya memang terdengar lebih keras, tetapi kanal stereonya hilang. Kami saling tertawa getir. Satu masalah teknis “terselesaikan” di ruang kami, tetapi menjelma masalah baru di ruang tetangga. Begitulah produksi BJ18 hari-hari itu: menambal lubang di satu sisi, membuka retak di sisi lain.
Pada suatu malam, mendengar cerita ini, seorang seniman lain yang karyanya juga semula akan dipresentasikan di Ndalem hanya tersenyum tipis, mungkin kelelahan setelah memindahkan karyanya seorang diri ke Karangkitri.

***
Di penghujung tulisan ini saya ingin bicara soal etika. Namun sebelum itu, saya perlu jujur kepada diri sendiri. Dalam kekacauan produksi BJ18, saya pun ikut berperan dalam reproduksi relasi kuasa yang timpang.
Satu peristiwa cukup membekas ketika tangkapan layar Google Docs internal kami, sebuah dokumen kerja berisi rancangan karya awal, tiba-tiba dipakai sebagai poster publik, padahal lebih dari dua puluh materi visual sudah kami kirim.
Emosi saya pecah. Saya menulis kepada salah seorang panitia, “Mau nanya, ini yang bikin dan ngelolosin poster otaknya di mana ya?” Ketika dijelaskan bahwa itu karya tim media dan sudah di-acc petinggi BJ18, saya masih menambahkan, “Kan sudah kami kasih materi visual. Kalian malah ngebocorin file dapur. Pakai sedikit otaknya, tim media.”
Kini saya melihat dengan lebih jernih bahwa amarah itu bergerak ke ruang yang keliru. Kekacauan di lapisan pengambil keputusan membuat pekerja lapangan—yang paling rentan, yang bekerja paling keras—menjadi pihak terdekat untuk menampung luapan frustrasi. Namun persoalan pokoknya tetap ada: publikasi dokumen internal adalah salah satu kesalahan fatal dalam penyelenggaraan pameran ini.
***
Persoalan saya, pada akhirnya, bukan hanya bahwa karya kami gagal tampil utuh. Bahkan seandainya proyek di Ndalem Brotoasmaran terwujud sepenuhnya, saya sendiri tak pernah yakin bahwa apa yang hendak kami sampaikan pasti dapat terkomunikasikan dengan baik kepada publik.
Seni memang selalu membawa risiko salah dengar dan bias tafsir. Namun dalam kondisi yang kami alami: karya terpotong, konteks tercerabut, dan presentasi terpecah, risiko itu menjelma keniscayaan. Sudah sejak awal goyah runtuh sepenuhnya di tahap penyajian.
Di sinilah kritik Ibrahim dan perhatian Darryl saling bertemu: tubuh presentasi yang ringkih bersumber dari proses produksi yang goyah. Kegagalan pamer bukan sekadar perkara teknis, tetapi gejala dari sistem kerja yang terlampau sentralistis tanpa distribusi tanggung jawab yang jelas.
Pada hari pembukaan 5 Oktober, sementara pembukaan berlangsung di Kampoeng Mataraman, saya di Monumen Bibis harus “memaksa” tukang dari vendor ikut membeli triplek sendiri karena panitia baru berencana mengadakannya esok hari. Beruntung, struktur utama partisi bisa rampung malam itu. Listrik juga akhirnya tersalurkan.

Komentar FX Harsono atas tulisan Darryl menegaskan garis yang sama: menampilkan karya dengan pantas berarti menghargai seniman dan, terutama, publik. Teknologi presentasi yang layak, tata ruang yang serius, informasi kontekstual yang memadai—semuanya bukan ornamen, melainkan prasyarat etika presentasi paling dasar. BJ18 dibiayai dana publik. Ia berasal dari warga yang berhak memahami apa yang mereka danai. Di titik inilah, setidaknya jika berkaca pada pengalaman karya kami, integritas penyelenggara terasa tiada.
SUR sendiri telah menyampaikan permohonan maaf secara formal kepada keluarga Ndalem Brotoasmaran, karena sempat melakukan produksi dengan asumsi keliru bahwa izin penggunaan ruang telah tuntas.
Saya menulis curhat colongan ini secara terbuka karena, ketika SUR menyiapkan karya di Cirebon sebelum BJ18 selesai, ada seseorang yang sama sekali tak terlibat BJ18 berujar kepada teman saya, “Katanya SUR galak, ya?”. Curhat colongan ini menjadi semacam aksi defensif saya untuk menjelaskan kenapa kami dianggap galak—atau cengeng nan ribet.
Barangkali diskursus seni kita akan bergerak lebih jauh jika gosip-gosip underground yang selama ini hanya berputar di kalangan tertentu ikut dipublikasikan.
Mungkin dari keterbukaan semacam itu justru lahir urgensi untuk membenahi hal-hal yang kerap dianggap remeh, bahkan dikecilkan.
Misalnya waktu kerja yang manusiawi, perangkat teknis yang layak, izin yang jelas, kontrak yang transparan, serta distribusi keputusan yang sehat, dan berbagai prasyarat lain yang telah disebut Darryl. Dari sanalah etika seni publik dapat bermula.
Keterbukaan ini semoga tak berhenti sebagai catatan, melainkan mendorong evaluasi serta pembongkaran cara kerja Biennale Jogja ke depan. Tanpa perubahan konkret, perdebatan makna hanya berputar sebagai gema rapuh di ruang tertutup, tak pernah menyentuh publik. Dari lantai pamer Monumen Bibis, slogan dekolonisasi masih terasa melayang jauh.
Editor: Arlingga Hari Nugroho
Foto sampul: Biennale Jogja 18





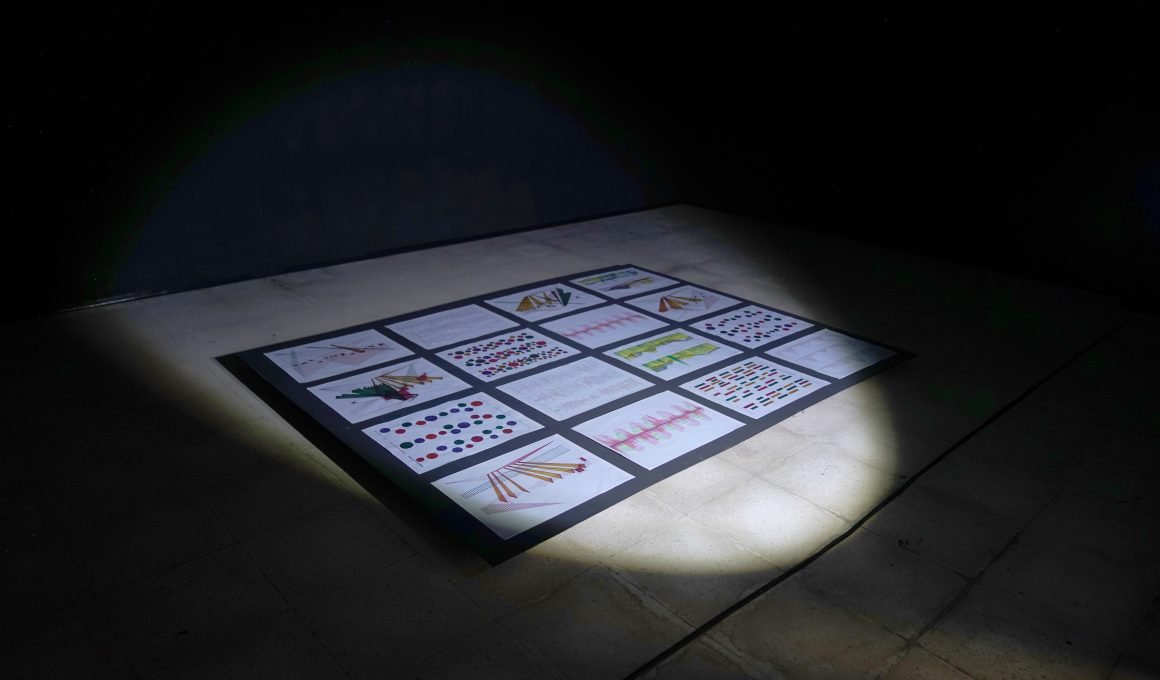






Sejauh ini antara hipotesis Ibrahim Soetomo, antitesis Darryl Haryanto & tanggapan dari Dhuha Ramdhani ini yg paling jujur. Semoga BJ18 jadi reflektor utk pelaku tata kelola pameran ataupun acara seni di Indonesia utk lebih berintegritas. Terlebih yg mendanai adlh rakyat.