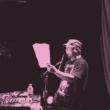Serius. Salah satu hal terpenting dari Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2025 ialah menjadi corong diseminasi pengetahuan lokal, paling tidak bagi saya. Dengan lokasi di Gunungkidul, FKY berhasil menjahit beragam pengetahuan: kosmologis, ekologis, kultural, hingga politis. Semua pengetahuan itu berbasis pada laku keseharian masyarakat Gunungkidul. Warga Gunungkidul. Cah Gunungkidul.
Selama tiga hari dua malam, saya hadir di FKY di Gunungkidul. Festival berlangsung dari 11-18 Oktober 2025. Dalam kurun waktu yang singkat, saya mencoba memahami dan merasakan bagaimana pengetahuan lokal bekerja dalam laku sehari-hari. Hasilnya, apa yang selama ini saya yakini sebagai mitos, mistis, dan istilah sejenisnya, buyar. Terobrak-abrik. Logika-logika yang awalnya saya yakini paling benar, menjadi hancur.
Kemudian, pertanyaannya adalah bagaimana pengetahuan lokal dan laku keseharian terangkum dalam satu festival kesenian-kebudayaan yang singkat?
Inilah beberapa catatan saya yang tentunya juga singkat. Catatan singkat tentang pertemuan dengan nilai dan pengetahuan baru.
Tak ada yang menyangkal bahwa Gunungkidul adalah satu kawasan terluas dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di sana, tertanam ragam adat, tradisi, sejarah, dan nilai, yang sudah hidup bersama warga selama puluhan, dan bahkan ratusan tahun.
Itu semua, tak hanya menjadi simbol masyarakat Gunungkidul, tetapi juga sebagai tata cara hidup. Dalam FKY 2025, laku itu ditampilkan dan diberi ‘panggung’, bahkan sejak sebelum gelaran dibuka. Ketika panggung dan stand-stand akan didirikan, satu prosesi ritual bernama Njawab dilangsungkan–peletakkan sesaji. Itu adalah cara kulo nuwun, cara meminta izin untuk sesaat memakai Lapangan Desa Logandeng, kepada entitas lain non-manusia yang sudah lebih dulu tinggal di sana.
Peletakkan sesaji tidak hanya dimaknai sebagai upaya permisi, tetapi juga usaha merawat hubungan yang tak melulu antar manusia. Entitas lain yang disebut penjaga atau roh adalah bagian dari kehidupan masyarakat di Gunungkidul.
Pada pembukaan pameran Gelaran Olah Rupa, secara simbolik dibuka pada Jumat malam 10 Oktober 2025, satu ritual kembali dilaksanakan. Tepat di depan pintu masuk ruang pamer, seseorang seperti mengucapkan jampi-jampi (mantra). Tidak jelas apa yang diucapkannya, tapi saya yakin itu adalah rapalan-rapalan doa. Semua mata yang turut hadir di situ, termenung memperhatikan, dan sesekali mendokumentasikan.
Setelah ritual selesai, saya mencoba bercakap dengan seorang kawan: “Kae mau sopo?”. Kawan saya menjelaskan bahwa seseorang itu adalah salah satu seniman residensi asal Taiwan yang sekaligus penghayat kepercayaan dari masyarakat adat Amis. Nama ritual yang ia lakukan adalah Mifetik.1

Meski usaha transenden itu bukan dari warga lokal, tetapi ada satu keyakinan bahwa roh mampu melampaui batas apa yang disebut ‘bahasa’ dan ‘gestur’ ritus.
Di Gunungkidul, bermacam ritual tumbuh subur. Ritual mewujud menjadi pengetahuan tempatan (local epistemology) yang diturunkan dari simbah atau nenek moyang. Saya mengetahui ihwal itu dari satu kawan yang tumbuh besar di kabupaten paling Timur di DIY ini.
Katanya, ada ratusan orang pemeluk penghayat kepercayaan—sebuah keyakinan spiritual di luar agama resmi versi negara—yang menempatkan ritual sebagai keseharian.
Apa yang disebut sebagai ritual, sebenarnya tak jauh berbeda dengan yang saya yakini sebagai sembahyang. Sama-sama memiliki kepercayaan, kepada Yang Agung atau Yang Maha Esa. Hanya saja caranya berbeda. Akan tetapi, saya melihat ritus yang dijalankan warga Gunungkidul—khususnya penghayat kepercayaan—, selalu memerhatikan aspek hubungan relasional antara manusia, alam, dan (roh) leluhur.
Hubungan ketiga entitas itu, menjadi bagian dalam FKY 2025. Salah satu presentasinya berupa karya yang dipameran dalam Gelaran Olah Rupa. Karya itu adalah hasil kolaborasi antara Resan Gunungkidul dan M. Shodik yang diberi tajuk Mambu Ampo, Geger Labuh, dan Genduren.

Karya kolaborasi tersebut, menunjukkan bahwa warga Gunungkidul, khususnya Resan Gunungkidul, memosisikan alam sebagai bagian dari kehidupan. Sebagai entitas yang memiliki agensinya sendiri. Bukan sumber daya alam yang bisa dieksploitasi. Hubungan relasional itu melihat alam, manusia, dan roh sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebagai jaringan yang saling terhubung, secara biologis maupun spiritual.
Hubungan yang menjadi nadi warga Gunungkidul tersebut, berbasis pada pandangan kosmologis jagad gede dan jagad cilik, atau dalam istilah barat, biasa disebut makrokosmos dan mikrokosmos. Bahwa, alam dan segala isinya—tanah, air, pohon—juga bagian dari tubuh yang harus diruwat dan dijaga.
Satu lagi, karya yang berbicara tentang pengetahuan tempatan, yang saya amati, adalah kolaborasi antara Survive! Garage bersama Mbah Bambang dan Mbah Saido (tokoh adat dari Tepus, Gunungkidul). Dalam karya berjudul Babad Sigare Bukit, Bayu Widodo (Survive! Garage) menceritakan kepada saya, bahwa mereka (re: masyarakat adat di Tepus) punya pengetahuannya sendiri dalam memprediksi alam, sifat seseorang, dan hari baik dengan teknologi bernama Pawukon.
Pawukon berbentuk seperti papan tatal yang terdapat kotak-kotak dan memiliki cara sendiri dalam hitung-hitungannya. Hitungan diperoleh dari melihat bintang, ombak laut, dan gerak arah angin. Di tengah situasi alam yang semakin terkikis di Gunungkidul bagian Selatan akibat pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), Pawukon masih relevan dan masih menjadi alat ampuh untuk memprediksi gejala-gejala alam.

Selain yang disajikan dalam Gelarah Olah Rupa, Lokakarya “Gunungkidulan” juga menjadi perkenalan saya dengan pengetahuan tempatan di tanah karst ini. Salah satu dari sekian banyak lokakarya, saya tertarik dengan Sesaji Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran bisa menjadi teropong untuk mengetahui keberagaman kepercayaan di Gunungkidul. Di sana dibagun pura, masjid, hingga peribadatan kejawen.
Di lokakarya tersebut, saya belajar untuk merangkai sesaji dengan ragam komposisinya. Setiap bagian dari sesaji menyimbolkan entitas, misalnya bunga dengan warna merah, adalah simbol dari dewa sebagai titik tertinggi peradaban. Sesaji ini biasanya digunakan untuk upacara adat, yang tak sekadar ritual persembahan, namun juga simbol syukur kepada alam dan Tuhan.
Lagi-lagi, relasi antara manusia, alam, dan roh atau Tuhan, menjadi nyawa peribadatan dan ritual bagi warga Gunungkidul. Di tengah arus modernitas dan hegemoni kepercayaan yang diproduksi oleh agama resmi versi negara, para penghayat kepercayaan di Gunungkidul tetap punya otonominya sendiri.

Pengetahuan tempatan menjadi nyawa sekaligus cara hidup warga Gunungkidul. Bahwa pengetahuan yang lahir dari tanah, dari hubungan kosmologis, dan dari leluhur, masih menjadi pegangan untuk terus mengingat pada nilai dan sejarah mereka sendiri.
FKY 2025 hanya berlangsung selama delapan hari, itu waktu yang singkat untuk merangkum ragam tradisi dan laku hidup yang ada di Gunungkidul. Namun, paling tidak, FKY mampu menghadirkan pintu gerbang untuk memahami segala pluralitas yang ada di Gunungkidul. Mempelajari pengetahuan tempatan dan membuka kemungkinan-kemungkinan lain dalam trayektori panjang kebudayaan.
***
- Mifetik adalah bentuk komunikasi spiritual yang dilakukan oleh setiap orang Amis. Selama Mifetik, roh-roh menyapa roh-roh tanah, leluhur, dan semua makhluk hidup yang hadir. Mereka mengumumkan pembukaan suatu acara dan berharap roh-roh ini akan memberkati dan memastikan kelancaran acara. ↩︎
Editor: Arlingga Hri Nugroho
Foto sampul: Bijaksana Creative – FKY 2025