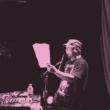Lanskap suara tak ubahnya vibrasi atas pengalaman tubuh dan ruang dengar. Panca indera menjadi yang menerima, katalis atas perjumpaan diri dan yang kosmis, begitu juga yang kini dan yang leluhur. Bebunyian tak hanya menjadi kawan perjalanan yang dicari, ditempatkan dan dimaknai, namun juga menjelma laku yang dihidupi sepanjang hayat oleh Rani Jambak-perempuan berdarah Minangkabau yang malam Rabu (15/10) hadir membawa cerita untuk dibagi.
Menaiki tangga kayu Galeri Lorong, saya memasuki ruang kosong dan lapang. Karpet tergelar, dibersamai langkah anak kucing yang tak bisa diam kesana kemari. Pengeras suara dan layar proyektor menampilkan sajian visual dan auditif, sebuah tradisi mingguan Geleri Lorong bertajuk vakansi sonik yang digelar di bawah langit distrik Nitiprayan, Yogyakarta.
Sekitar sepuluh orang duduk di posisi, kaki bersila dalam ragam pose yang tak begitu terlihat di tengah ruang gelap. Cahaya lampu dimatikan, sumber cahaya dan suara terpusat di satu titik. Selama 43 menit sesi dengar berlangsung khusyuk, asing, menegangkan, terapeutik, sekaligus nostalgis di saat yang sama. Bebunyian bercampur dalam kontur yang rapat, tanpa pakem maupun penalaan. Ada kemurnian yang muncul kala video memperlihatkan Rani dengan alat perekam suaranya, mendatangi tiap titik di berbagai teritori Indonesia untuk mencatat bunyi, mengarsip suara yang bisa ia temukan.
Suara debur ombak, dunia luar dan alam bebas, membaur dengan tatalu, tak lupa bebunyian suara elektronik yang turut masuk. Soundscape atau pemandangan bunyi sering muncul sebagai istilah yang familiar, namun berbeda kali ini. Bunyi rebab juga muncul bersama alunan vokal tradisi yang belum pernah saya kenal sebelumnya.

Di babak kedua, diputar satu album penuh bertajuk “Vibra Genetika”, album yang menjadi anak kandung Rani sendiri-sebuah mahakarya yang lahir lewat perjalanan panjang. Sebuah pencarian jati diri— menggali akar Keminangkabauan melalui bunyi. Saat itu saya sadar bahwa lokalitas dan kedirian bisa terproyeksi dalam bentuk yang berbeda. Tidak melulu lewat kebakuan dan struktur yang kadang malah mengekang.
Dalam “Vibra Genetika”, tersemat beberapa judul seperti Joget Sumatra, Merantau, hingga Kembang Mengembang. Masing-masingnya memuat spektrum sonik yang menarik sekaligus enigmatik. Di sela-sela track masuk suara wawancara penduduk lokal, bunyi alat menenun songket, hingga instrumen tiup dan perkusi. Tak ada kadens atau pun coda, tiap track berhenti tanpa benar-benar bisa diprediksi.
Setelah itu sesi diskusi dimulai. Para peserta diminta melontarkan pendapat atas pengalaman auditif yang dirasakan. Tanggapannya beragam, mulai dari perasaan dijajak masuk ke dalam perjalanan, nostalgia, hingga atmosfir yang belum pernah ditemui sebelumnya. Rani bercerita referensinya, salah satunya Björk yang merupakan musisi elektronik asal Iceland.
Ada dunia yang baru bagaimana bebunyian dalam horizon pengalaman Rani bisa begitu kuat dan menyimpan penjelasan untuk saya cerna satu persatu. Minangkabau terasa begitu jauh, begitu juga Kota Medan yang ia tinggali. Namun lewat suara-suara yang ia arsip dan presentasikan, saya memahami kalau pemandangan bunyi punya tempat yang luas sekaligus personal untuk dijelajahi.
Paradigmanya tidak lagi sesempit dualitas antara tradisi dan modern. Jauh melampaui itu, kesempatan untuk mengenal diri sendiri mewujud lewat eksplorasi musikal yang meruntuhkan sekat-sekat eksklusivitas maupun konvensi. Tidak menyingkirkan satu sama lain, tidak pula mensubordinasi satu sama lain. Bebunyian hadir secara spasial mengitari lanskap sosial dan kebudayaan sehari-hari—sedari kecil hingga bertumbuh menginjak masa dewasa.
Segala sesuatu yang kita alami hari ini, menurut Rani selalu terhubung dengan apa yang leluhur kita alami juga di masa lalu. Satu alasan mengapa nama albumnya “Vibra Genetika”, disebabkan keyakinannya bahwa manusia menyimpan dan mewarisi vibrasi secara genetik secara turun temurun.
Apa yang ia sukai dan kerjakan sejatinya juga terhubung dan pernah dilakukan oleh leluhurnya di masa silam.
Rani bercerita tentang Rabab (rebab) asal Minangkabau yang terbuat dari batok kelapa dan dimainkan sembari bernyanyi. Alat musik yang membutuhkan teknik dan keterampilan dalam memainkannya, sehingga tak banyak yang menjadi musisi rabab di generasi muda. Dalam ceritanya juga ia berbagi tentang kebudayaan di lanskap pesisir Minangkabau, salah satunya para nelayan yang membagi hasil laut dan boleh dengan bebas diambil oleh masyarakat. Itu tampak dalam rekaman babak pertama yang juga menampilkan bebunyian kayu kapal yang dipasang, dipaku dan menghasilkan gejala ritmikal yang khas. Sungguh malam yang memberi daya hidup dan bersuara tentang cara pandang baru mengenai bunyi.

Sehari setelahnya saya mendatangi Kincia, sebuah karya seni instalasi milik Rani Jambak yang dipasang di dalam ruang pamer The Ratan Biennale ke-18 Jogja. Saya merasakan pengalaman yang lebih imersif dan organik. Bebunyian bersumber langsung dari objek-objek yang dipresentasikan, termasuk instrumen talempong dan tombol-tombol dengan fitur untuk mengganti varian bebunyian yang juga diperdengarkan dengan bantuan pengeras suar. Kincia memperlihatkan bangunan artistik berbentuk kincir yang menjadi focal-point ruang pamer. Kincirnya terus berputar dan ragam bunyi bersahutan melatari ruangan yang saya kelilingi dan jamah di tiap sudutnya.
Dalam kebudayaan Minangkabau, Kincia digunakan para petani untuk mengairi sawah dan sayangnya kini sudah terancam punah. Melalui karya ini, Rani bersuara soal pentingnya merawat warisan pengetahuan lokal.
Saat ini, Rani sedang menjalani studi doktoral di Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada. Salah satu misinya adalah repatriasi warisan suara untuk megembalikan arsip bunyi yang tersimpan di Belanda, terutama yang dihimpun oleh etnomusikolog Jaap Kunts di masa silam. Sudah lama saya tidak mendengar nama Jaap Kunts, setidaknya sejak lulus kuliah dan kurang terpapar dengan dunia akademik musik. Nama itu kembali muncul dan terucap di tengah obrolan malam di Galeri Lorong—memberi gairah untuk kembali menelusuri dunia di balik pengetahuan lokal—sebuah teritori tak terjamah dan penuh kisah.
Perjumpaan dengan Rani Jambak mendorong pemaknaan ulang yang penting soal ruang dengar dan identitas. Suara (bunyi) bisa jadi jalan pencarian atas banyak hal, menaut dengan yang spritual, kosmik, hingga yang paling hakikat tentang siapa diri kita sesungguhnya. Saya ingat Rani bilang ketika kita berada di antara laut, begitu mudahnya ia menenggalamkan manusia. Begitu kecilnya kita di tengah semesta yang membentang luas, tapi begitu besarnya ego dan kesombongan yang bersemayam dalam diri. Itu yang juga saya refleksikan. Mengenal jejak leluhur, barangkali menjadi cara untuk tetap menapak bumi, menumbuhkan empati, dan memberi ruang untuk suara-suara yang jarang kita dengar.
Editor: Arlingga Hari Nugroho
Foto sampul: Yes No Klub/Swandi Ranadila