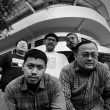Dalam ulasan ini Gita Dananjaya mengajak kita menyelami Jalaran Sadrah, album terbaru dari Barasuara yang dirilis tahun 2024 lalu, sebagai ruang imajinatif sekaligus cermin bagi kegelisahan manusia modern. Bukan hanya bicara soal komposisi musik atau lirik, tulisan ini menggali lapisan-lapisan makna yang lesap dalam siklus kehidupan yang tak terhindarkan.
Pertanyaan Pertama – Antea
“Untuk apa terus mencoba jika dunia hanya sementara?”
Dunia kini terasa aneh bagi Sadrah. Seolah-olah waktu berjalan di tempat, memutar ke arah yang sama tapi tak pernah membawa perubahan berarti. Langit di atas kota kadang-kadang terasa terlalu berat, seakan-akan bisa jatuh kapan saja. Sadrah berjalan di antara bangunan-bangunan yang seolah bergerak, dinding-dindingnya bergeser seperti hidup. Tak ada yang memperhatikan selain Sadrah. Manusia di sini terlalu sibuk mengejar bayangan yang mereka sendiri ciptakan, terlena oleh keangkuhan yang tak mereka sadari sedang menggerogoti dari dalam.
Sadrah sering berpikir, untuk apa semua ini? Hidup sementara, ditipu oleh keindahan yang dangkal. Dikelabui oleh dunia. Bahkan ketika Sadrah mencoba bertanya pada dirinya sendiri, mengapa Sadrah masih mencoba, jawabannya selalu kabur. Hanya kematian yang menang atas segalanya.
Ketika matahari mulai turun dan kota ini diselimuti cahaya jingga yang terdistorsi oleh asap kota, Sadrah melihat sesuatu. Sosok bayangan. Sadrah pernah melihatnya sebelumnya, berkelebat di sudut pandangnya. Namun hari ini, bayangan itu sedikit lebih jelas. Bentuknya seperti kabut tebal yang dipahat menjadi manusia tanpa wajah. Bayangan itu melayang di atas tanah, mengikutinya dari kejauhan.
Sadrah mempercepat langkah, mencoba mengabaikannya. Namun semakin Sadrah melangkah cepat, semakin dekat bayangan itu. Sampai akhirnya, ia ada tepat di samping Sadrah, mengikuti gerakannya dengan lancar. Sadrah bisa merasakan kehadirannya, seperti angin dingin yang tiba-tiba muncul meski udara di sekitar begitu terik. Sadrah tidak bisa mengusir perasaan bahwa bayangan itu adalah cerminan dari sesuatu yang lebih dalam.
“Untuk apa kau terus mencoba?” Suara itu datang dari arah bayangan, lirih tapi jelas. Sadrah tertegun, lalu menoleh. Tak ada apa-apa di sana, hanya jalan kosong dan deretan toko yang tutup. Namun Sadrah tahu, suara itu nyata. Suara itu mengingatkan bahwa semua ini sementara. Hidup, pencarian, bahkan dunia yang dirasa begitu nyata, semua akan hancur menjadi debu suatu saat nanti.
Di penghujung jalan, Sadrah tiba di apartemen tua yang kumuh, di mana jendela-jendelanya dipenuhi debu dan catnya terkelupas di sana-sini. Apartemen ini sudah tua, seperti segala sesuatu di kota ini, tapi tetap berdiri, menolak untuk runtuh meski dilahap oleh waktu. Begitu Sadrah masuk ke dalam, bayangan itu menghilang, tetapi Sadrah tahu itu hanya sementara. Seperti segalanya di kota ini.
Kamar yang Sadrah tempati tidak besar, hanya cukup untuk satu manusia. Dinding-dindingnya dipenuhi retakan. Sadrah duduk di tepi ranjang dan memandang keluar jendela. Di luar sana, dunia bergerak dengan ritme yang aneh, seolah-olah semuanya hanyalah ilusi.
Malam tiba, dan kota mulai berubah lagi. Suara yang semula memenuhi jalanan mulai menghilang, digantikan oleh keheningan yang terasa tidak wajar. Lampu-lampu jalan berkedip, lalu padam, menyisakan kegelapan yang semakin pekat. Dalam kegelapan itu, Sadrah mendengar suara yang sama seperti sebelumnya. Suara yang bertanya, mengapa Sadrah terus mencoba. Namun kali ini, Sadrah tak lagi takut. Mungkin inilah saatnya untuk bertanya balik.
“Apa yang kau inginkan dariku?” bisik Sadrah pada suara itu.
Tidak ada jawaban, tapi Sadrah tahu, dalam diam, bahwa yang sedang berbicara kepadanya, atau mungkin menertawakannya adalah Kematian. Hidup ini sementara. Dan Sadrah mengaku diri, hanya debu dalam kerasnya dunia.
Pertanyaan Kedua – Etalase
“Sampai kapan kita terus berpura-pura?”
Di tengah hiruk pikuk kota yang tak pernah tidur, manusia hanyalah pameran. Manusia-manusia berderet di balik kaca etalase, menampilkan kepalsuan yang mereka banggakan. Jalan-jalan dipenuhi senyuman yang tak pernah sampai ke mata, sementara di dalam hati, kesunyian berkuasa. Setiap hari, mereka berjalan dengan langkah yang seragam, seolah dunia ini adalah panggung yang sudah diatur naskahnya sedari lama.
Sadrah melangkah melewati deretan etalase, melihat bayangan dirinya sendiri terpantul di kaca-kaca toko yang mengilap. Ada ribuan wajah di sana, semua tersenyum tapi tak ada yang bahagia. Di balik kaca, Sadrah melihat mereka yang terus mencari cara, mencoba membuktikan sesuatu yang tidak pernah ada. Dunia ini seperti labirin penuh pantulan. Mereka semua berusaha menemukan jalan keluar, tapi hanya terjebak dalam bayangan diri sendiri.
“Bagai katak dalam tempurung,” gumam Sadrah lirih, mengingat pepatah lama yang sering kali terlintas di benaknya. Mereka merasa penting, namun sesungguhnya mereka hanyalah tumbal kecil dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan.
Di suatu persimpangan jalan, Sadrah berhenti. Di depan sebuah etalase besar, ada sekelompok manusia yang mengerumuni sesuatu. Mereka tertawa, berbicara dengan suara keras, membandingkan barang-barang yang dipajang. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Barang-barang mahal, berkilau, mewah, tampilan kehidupan yang tampaknya ideal. Namun Sadrah tahu lebih baik. Sadrah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum mereka.
Mereka semua hidup dalam kebohongan, pikir Sadrah. Setiap hari, mereka berlomba menjadi yang terbaik, menilai diri mereka berdasarkan prestasi, popularitas, harta. Dan ketika mereka gagal, mereka berpura-pura tidak melihat, menutupi kekurangan mereka dengan kepalsuan yang lebih tebal. Mereka semua lelah, tapi tak ada yang berani mengakui.
Sadrah berjalan lebih dekat, mendekati sekelompok manusia yang sedang berdiskusi di depan etalase. Mereka berbicara tentang harga, tentang status, tentang bagaimana barang-barang yang mereka lihat akan membuat hidup mereka lebih baik. Namun Sadrah hanya melihat bayang-bayang dari mereka, jiwa-jiwa yang terperangkap dalam permainan tanpa ujung.
“Apa kau tidak lelah?” tanya Sadrah pada salah satu dari mereka, meski Sadrah tahu ia tak akan mendengarnya. Dan benar. Suara Sadrah tenggelam di antara obrolan mereka, tak seorang pun yang menoleh. Sadrah hanyalah suara di tengah ribuan suara lain, tidak lebih dari itu.
Hari semakin gelap, dan cahaya dari etalase mulai memudar. Manusia-manusia mulai pergi satu per satu, tapi Sadrah tetap berdiri di sana, memandang dirinya sendiri di kaca. Seperti manusia lain, Sadrah juga bagian dari etalase ini. Sadrah juga terjebak, meski Sadrah berusaha keras menyangkalnya.
“Kehidupan adalah sebuah pameran, dan kita semua pemerannya. Namun tak ada yang benar-benar tahu, apakah kita yang dipamerkan atau justru yang memamerkan diri sendiri. Membandingkan dan pengakuan tak henti-henti diucap dan diharap. Setiap hari kita mengukur diri kita berdasarkan standar yang ditentukan oleh manusia lain, oleh masyarakat, oleh dunia yang tak pernah berhenti menuntut lebih.”
Malam mulai menyelimuti kota. Sadrah melangkah menjauh dari etalase itu, meninggalkan bayangannya di kaca. Di kejauhan, lampu-lampu jalan mulai menyala, memberikan cahaya redup di tengah keseragaman yang mencekam. Sadrah melangkah ke arah rumah, diiringi oleh suara-suara samar di sekelilingnya.
Ketika Sadrah sampai di apartemen, Sadrah merasa hampa. Dunia di luar seolah masih terus berputar, tapi di dalam sini, semuanya diam. Sadrah menutup pintu, meninggalkan segala kepalsuan di baliknya. Namun Sadrah tahu, tak peduli seberapa keras Sadrah mencoba, dunia ini selalu mengikutinya, seperti bayangan yang tak bisa disingkirkan.
Malam semakin larut, dan Sadrah hanya bisa memandang keluar jendela. Dalam hening, Sadrah bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya manusia cari dalam hidup ini? Dan sampai kapan manusia akan terus berpura-pura?

Pertanyaan Ketiga – Merayakan Fana
“Pernahkah kau menari dalam kefanaan?”
Malam itu terasa berbeda. Angin yang biasa membawa hawa dingin kini berhembus lebih lembut, seakan menggandeng jiwa-jiwa yang terjebak di antara dunia nyata dan dunia mimpi. Sadrah berjalan sendiri, melintasi jalanan kosong, sementara di atas sana, langit hitam membentang tanpa bintang. Kota ini seperti terbungkus kabut yang tak kasat mata. Sulit dibedakan mana yang nyata dan mana yang hanya khayalan.
Setiap langkah membawa Sadrah lebih dekat pada sesuatu yang tak terlihat, namun begitu nyata di dalam benaknya. Ada rasa tak kekal yang meresap di udara, membiaskan batas antara hidup dan mati. Senyum abadi yang pernah Sadrah lihat dulu, kini hanya tinggal bayangan di ingatan, tersimpan di sudut yang jauh dan berdebu. Sadrah bertanya-tanya, apakah aku satu-satunya yang merasakan ini, atau semua manusia di dunia ini juga hidup dalam pencarian tanpa akhir?
Sadrah terus melaju, mencoba menembus batas sepi yang semakin menekan. Perbedaan ruang dan waktu kini tak ada artinya, semuanya terasa kabur. Di persimpangan jalan antara kenyataan dan mimpi, Sadrah berhenti. Di sana, di tengah kekosongan yang begitu mencekam, Sadrah memperingati sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Fana—itu yang ia temukan.
Di depan mata Sadrah, warna-warni pelangi mulai muncul, melingkupi segala yang ada. Sadrah terhanyut dalam keindahan yang tak terduga, sebuah perayaan fana yang membuat segalanya terasa begitu nyata namun sekaligus tidak berwujud. Setiap langkah yang Sadrah ambil membiaskan realitas lebih jauh lagi, membawanya pada dimensi lain yang hanya bisa dijangkau melalui perasaan yang mendalam.
Di sana, Sadrah menemukan-NYA—Penguasa jiwa-jiwa yang hilang, Pencipta kehidupan dan kematian. DIA tak berkata apa-apa, hanya memandang Sadrah dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. Sadrah tahu, di sinilah semua jiwa akan kembali pada akhirnya. Kesendirian yang selama ini menemani Sadrah di dunia nyata kini menemukan maknanya di sini. Di sini, Sadrah tidak sendiri. Ada ribuan jiwa lain yang juga merayakan kefanaan mereka, menari dalam keremangan.
Perlahan, Sadrah mulai memahami bahwa hidup ini memang fana. Semua yang manusia anggap penting hanyalah mimpi yang akan lenyap seiring berjalannya waktu. Perjuangan manusia untuk menemukan makna, untuk memahami hidup dan mati, hanyalah bagian dari perjalanan menuju kesadaran bahwa tak ada yang abadi. Manusia hanyalah debu dalam semesta.
“Namun di balik kefanaan itu, ada keindahan yang luar biasa. Keberadaan kita yang rapuh justru membuat setiap momen terasa lebih berharga. Di tengah gelap dan terang, kita menemukan makna hidup, meskipun hanya sementara. Dan mungkin, itulah yang membuat hidup ini layak dirayakan.”
Ketika Sadrah tersadar kembali ke kenyataan, perasaan tenang menyelimuti hatinya. Fana bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dalam kefanaan itulah Sadrah menemukan kekekalan yang sebenarnya.
Malam terus beranjak, dan angin yang tadi membelai kini semakin dingin. Sadrah memandang ke langit yang kosong, memikirkan perjalanannya. Di sana, di balik gelapnya langit, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Dan dalam diam, Sadrah tersenyum, merayakan kefanaannya.
Pertanyaan Keempat – Habis Gelap
“Apakah masih ada yang peduli?”
Langit kelabu menggantung rendah, seolah-olah menekan kota di bawahnya. Jalan-jalan tampak sunyi, tak ada suara, hanya bisikan angin yang menyusup di antara reruntuhan bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Di kejauhan, terdengar gemuruh samar, bukan suara hujan, melainkan sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, seperti gelombang amarah yang siap menghancurkan apa saja yang dilewatinya.
Sadrah berdiri di ambang pintu sebuah rumah kosong, matanya menatap hampa ke luar. Dunia ini, yang dulu pernah penuh dengan harapan, kini berubah menjadi ladang kematian. Kemanusiaan terkubur di bawah reruntuhan perang dan kehancuran. Sadrah memejamkan mata, mencoba mengusir gambaran mayat-mayat yang tertinggal di jalanan, wajah-wajah tak berdosa yang terhapus oleh kekejaman dunia yang tak mengenal ampun.
“Ini adalah akhir,” gumam Sadrah pada dirinya sendiri, meskipun jauh di dalam hati, Sadrah tahu bahwa akhirnya tak pernah datang dengan mudah. Selalu ada sesuatu yang tersisa, sepotong harapan yang rapuh, seperti nyala lilin di tengah badai. Namun apakah manusia masih berhak berharap? Di dunia yang hanya menyembah uang dan senjata, apakah manusia masih punya alasan untuk bermimpi?
Setiap hari, suara-suara jeritan menggema dari sudut-sudut yang tersembunyi, jeritan anak-anak yang kelaparan, tangisan orang tua yang kehilangan segalanya. Meski begitu, tidak ada yang berubah. Mesin-mesin bengis terus melindas, menghancurkan tanpa ampun. Sadrah sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah masih ada yang peduli? Apakah ada yang tersisa dari kemanusiaan manusia, atau semuanya sudah lenyap, tenggelam dalam lautan keserakahan?
Namun di tengah gelap ini, Sadrah bertemu mereka, manusia-manusia yang masih berjuang meskipun dengan harapan yang nyaris habis. Mereka, yang memilih untuk melawan meski tahu bahwa akhirnya tiada terang. Mereka, yang terus berjalan di atas ribuan mayat, meskipun hati mereka hancur dan tercekat. Mungkin mereka bodoh, atau mungkin mereka adalah satu-satunya yang masih mengingat apa artinya menjadi manusia.
Sadrah berjalan bersama mereka sekarang, menyusuri lorong-lorong kota yang penuh reruntuhan. Setiap langkah terasa berat, tapi mereka tidak berhenti. Di mata mereka, Sadrah melihat bayangan-bayangan yang sama seperti yang pernah ia lihat di dalam dirinya sendiri. Kemarahan, kepedihan, namun juga tekad yang tak bisa dipadamkan.
“Kita tidak akan menyerah,” salah satu dari mereka berkata, suaranya parau, penuh kelelahan. “Meskipun kita tahu tidak ada cahaya di depan, kita akan terus berjalan.”
Sadrah mengangguk, meski hati kecilnya meragukan kata-kata itu. Bagaimana mungkin manusia berharap pada sesuatu yang tak pernah datang? Bagaimana mungkin manusia terus berjalan ketika dunia di sekitar sudah berubah menjadi neraka?
Namun, mereka tetap berjalan. Dan Sadrah, dengan segala keraguan dan ketakutannya, ikut melangkah di belakang mereka. Dalam setiap langkah, Sadrah mulai merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kekuatan yang datang bukan dari harapan, tetapi dari keputusasaan.
Mungkin sebaiknya manusia binasa, pikir Sadrah, karena dunia ini sudah terlalu rusak untuk diselamatkan. Di dalam hati kecilnya, Sadrah tahu bahwa bahkan dalam kehancuran, ada sesuatu yang patut diperjuangkan. Mungkin bukan untuk manusia saat ini, tapi untuk manusia yang akan datang. Mungkin, meski habis gelap, suatu hari akan ada yang menemukan cahaya.
Jeritan anak-anak kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih menyayat. Sadrah menutup telinganya, tapi suara itu tidak bisa dibungkam. Ini adalah kenyataan yang harus manusia hadapi. Dan dalam jeritan itu, Sadrah menemukan alasan untuk terus melangkah.
Malam semakin gelap, dan kilat cahaya sesekali menyinari langit. Namun, terang itu hanya sekejap, seperti harapan yang hampir padam. Sadrah tahu, di balik setiap kegelapan, ada sesuatu yang menunggu. Mungkin itu bukan terang, mungkin hanya bayangan. Namun selama Sadrah bisa melihat, selama Sadrah bisa mendengar suara manusia-manusia yang masih bertahan, Sadrah akan terus berjalan.
Di saat itulah Sadrah menyadari, meski habis gelap, kita semua, manusia, tanpa sadar, sedang mencari secercah terang, sekecil apa pun itu.

Pertanyaan Kelima – Fatalis
“Pernahkah kau merindu?”
Hari itu langit cerah, namun di bawahnya, suasana terasa begitu suram. Di sudut-sudut kota, manusia-manusia berjalan seperti bayangan, terjebak dalam rutinitas tanpa arah. Kabar tentang penyakit mematikan yang melanda setiap sudut kota sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, seolah-olah kematian adalah sesuatu yang wajar. Hanya soal waktu sebelum manusia tersentuh oleh cengkeraman maut.
Sadrah duduk di kursi kayu di tepi jendela, memperhatikan manusia-manusia yang lewat. Wajah-wajah yang kosong, tak lagi mencerminkan apa pun selain ketakutan yang disembunyikan di balik senyuman tipis. Di balik semua itu, ada semarak berlebihan yang menyelimuti kota. Manusia-manusia tampak seperti merayakan sesuatu yang tak terlihat, mungkin karena kebebasan semu yang mereka rasakan setelah begitu lama terkungkung.
“Ini semua hanya sementara,” gumam seseorang di belakang Sadrah. Sadrah menoleh dan melihat seorang wanita, wajahnya dipenuhi keriput, matanya kosong seperti kaca. “Kebebasan yang mereka rayakan itu hanya khayalan. Pada akhirnya, kita semua akan jatuh kembali ke dalam kegelapan.”
Sadrah terdiam, memikirkan kata-katanya. Sadrah tahu dia benar. Setiap langkah yang ia ambil di jalan-jalan ini terasa seperti pertaruhan, apakah aku akan selamat atau akan jatuh ke dalam jerat kematian yang terus mengintai di udara?
Benar. Di jalan, manusia bertaruh, bertarung, tanpa henti. Segala yang dilakukan manusia menjadi pengingat bahwa dunia ini adalah medan pertempuran, bukan hanya melawan penyakit atau maut, tapi juga melawan diri sendiri.
Sadrah bangkit dari kursi, bergabung dengan arus manusia-manusia yang berjalan tanpa tujuan. Di antara mereka, Sadrah melihat wajah-wajah yang ia kenal. Mereka yang dulu penuh keyakinan, sekarang berubah dan menyerah pada nasib. Mereka yang dulunya percaya pada kehidupan, sekarang hanya berharap agar semua ini cepat berakhir, tanpa peduli apakah yang datang setelahnya adalah kehancuran.
“Apakah kau juga menjadi fatalis?” tanya Sadrah pada seorang pria yang berdiri di sudut jalan, wajahnya tertutup masker yang sudah kotor oleh debu dan keringat.
Pria itu tersenyum pahit, terlihat dari sorot matanya. “Kita semua? Saat ini, bukan? Tidak ada lagi yang bisa kita percaya. Informasi begitu banyak, tapi kebenaran begitu sulit ditemukan. Semua manusia berlomba menjadi benar, tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi.”
Sadrah mengangguk. Dunia telah berubah menjadi tempat di mana manusia semua hidup dalam ketidakpastian, saling bertaruh antara kehidupan dan kematian. Setiap hari, manusia harus membuat keputusan, berharap bahwa keputusan itu adalah yang benar, meskipun pada akhirnya, manusia hanya mengandalkan naluri.
Langkahnya membawa Sadrah ke sebuah taman kecil, tempat di mana dulu manusia-manusia biasa bermain, tertawa, dan menikmati hidup. Kini taman itu sunyi, hanya beberapa manusia yang duduk terpisah satu sama lain, menatap kosong ke depan. Mereka yang bertahan adalah mereka yang sudah kehilangan harapan, tapi tetap hidup karena tak ada pilihan.
Sadrah berhenti di bawah pohon besar, menatap ke atas. Daun-daun berguguran perlahan, tertiup angin sejuk yang membawa rasa hampa. Di sinilah, dalam kesunyian ini, Sadrah merasakan betapa dekatnya kematian. Bukan kematian yang datang dengan rasa takut, tapi kematian yang hadir sebagai teman lama, seperti sesuatu yang selalu ada di sudut mata, menunggu waktu yang tepat untuk menyapa.
Sambil duduk termangu, Sadrah memandang sekitar. Wajah-wajah yang pernah ia cari di tengah keramaian kini hanya tinggal kenangan. Mereka yang sudah pergi, tak akan kembali. Mereka yang masih bertahan, hidup dalam bayangan masa lalu. Dan Sadrah, yang terus mencari, hanya menemukan kehampaan di mana-mana.
“Apakah kau juga merasa rindu?” suara seseorang membuyarkan lamunannya. Sadrah menoleh dan melihat seorang wanita duduk di bangku taman, tak jauh darinya. Wajahnya tersembunyi di balik kerudung hitam. Suaranya lembut, tapi penuh dengan kepedihan yang begitu dalam.
Sadrah tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Rindu telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Rindu pada mereka yang tak lagi ada, rindu pada kehidupan yang dulu pernah manusia miliki. Namun rindu itu tak pernah terpuaskan, karena yang manusia rindukan sudah hilang, lenyap bersama waktu.
Wanita itu bangkit dari tempatnya, berjalan mendekati Sadrah. “Kita semua sama,” katanya, suaranya hampir seperti bisikan. “Kita semua merindukan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Apakah kita akan terus hidup dengan rindu, atau akan menemukan sesuatu yang baru untuk kita perjuangkan?”
Pertanyaannya menggema di kepala Sadrah, namun Sadrah tak punya jawaban. Dunia ini telah berubah begitu banyak, dan Sadrah tidak tahu apakah masih ada sesuatu yang patut diperjuangkan. Namun di balik semua ketidakpastian ini, Sadrah tahu satu hal. Sadrah merindukan senyuman yang dulu selalu ia temukan di tengah keramaian.
Senja mulai turun, langit perlahan berubah menjadi biru kehitaman. Di kejauhan, suara riuh rendah mulai terdengar, suara manusia-manusia yang mencoba melawan ketidakpastian dengan cara mereka sendiri. Semarak sementara, pikirnya. Ini semua hanyalah pesta kecil yang akan segera berakhir, dan manusia akan kembali pada realitas yang tak terhindarkan.
Namun, untuk sekarang, Sadrah akan terus berjalan. Sadrah akan mencari wajah yang ia rindu di tengah kehampaan ini, meskipun Sadrah tahu mungkin tak akan pernah ia temukan. Dan ketika waktu akhirnya tiba, ketika semua ini berakhir, mungkin semua manusia akan menyadari bahwa yang manusia cari selama ini bukanlah jawaban, tapi hanya kesempatan untuk terus hidup, meski hanya sementara.
Pertanyaan Keenam – Biyang
“Sudahkah kau mendengarkan?”
Di balik kabut yang tebal, samar-samar terdengar kidung yang menenangkan. Suaranya mengalun, merambat di antara pepohonan yang berdiri sunyi di tepi jalan. Malam itu begitu gelap, meski bulan masih bersinar di atas sana. Sadrah berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak yang asing, menelusuri asal suara yang sepertinya tak pernah hilang dari telinganya.
Angin berhembus lembut, namun dinginnya menusuk hingga ke tulang. Dalam resah yang membungkus, Sadrah merasa semakin kecil, seperti diserap oleh dunia yang kian tak terjangkau oleh akal. Kabut kian pekat, dan langkahnya kian terasa berat. Namun suara itu, suara kidung yang terus berkumandang, seolah memanggilnya untuk terus maju.
Terang yang mengiringi langkah, suara yang merdu, bertalu-talu dalam pikiran Sadrah. Di balik kabut ini, Sadrah tahu ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang telah lama ia tinggalkan namun selalu ia rindukan.
Tiba-tiba, di depan Sadrah muncul bayangan seorang wanita tua, wajahnya berselimutkan kerudung merah gelap. Dia berdiri di bawah pohon besar yang menjulang tinggi, tangannya terangkat seolah sedang memanggil Sadrah. “Ana kidung rumeksa,” katanya perlahan, dengan suara yang begitu akrab. “Dian Kunthi, Ibu Bumi, Ibune Pandhawa.”
Sadrah berhenti di tempat, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Kata-katanya terasa seperti mantra kuno, penuh dengan makna yang tersembunyi. Di balik matanya yang dalam, Sadrah bisa melihat kearifan yang tak terukur. Wanita itu, sosok yang tampak lemah, adalah perwujudan dari kekuatan yang tersembunyi di balik alam ini. Sebuah kekuatan yang selalu ada, namun seringkali tak terlihat.
“Ibuku, kowe lan kabeh,” bisiknya, dan seketika itu Sadrah merasa seperti anak kecil yang kembali ke pelukan ibunya. Sadrah merasa aman, terlindungi, meski dunia di sekitar penuh dengan kecemasan. Wanita itu adalah representasi dari alam, dari semua hal yang mendasar dan murni, sesuatu yang telah lama Sadrah lupakan di tengah hiruk-pikuk kehidupan.
Dia mendekati Sadrah, menaruh tangannya yang lembut di kepala. Sentuhannya begitu menenangkan, seperti belaian seorang ibu yang menghapus segala kegelisahan. “Nanging sastra nala pathi,” katanya sambil menatap jauh ke depan. “Tansah setya mangaribawani.”
Sadrah menunduk, meresapi setiap kata yang dia ucapkan. Ada sesuatu yang mendalam di balik ucapannya, sesuatu yang tak hanya berbicara tentang hubungan antara manusia dan alam, tapi juga tentang takdir yang tak bisa dihindari. Alam, seperti ibu yang menjaga anak-anaknya, selalu setia meski manusia sering kali mengabaikan atau merusaknya.
“Pesan ini,” lanjutnya, “mengurai asa yang kau simpan begitu dalam. Dunia ini selalu penuh dengan kekacauan, namun di dalam kekacauan itulah kau bisa menemukan ketenangan. Kau hanya perlu mendengarkan.”
Kata-katanya menyentuh hati Sadrah. Sadrah merasakan beban di dada perlahan menghilang, seolah-olah semua kecemasan dan ketakutan yang menumpuk selama ini mulai larut. Ada kekuatan yang tersembunyi dalam kehadiran wanita ini, kekuatan yang memberi harapan, meski dunia tampak begitu gelap dan penuh ketidakpastian.
Wanita itu tersenyum, dan Sadrah melihat dalam senyumnya ada kebenaran. Kebenaran bahwa segala sesuatu yang manusia alami, baik kesedihan maupun kebahagiaan, hanyalah bagian dari siklus yang lebih besar. Dan dalam siklus itu, manusia bukanlah pemeran utama. Manusia hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar dari manusia itu sendiri.
“Berjalanlah dengan tenang,” katanya sebelum memudar kembali ke dalam kabut. “Dunia ini akan selalu berubah, namun peranmu di dalamnya tetap penting. Jangan pernah melupakan itu.”
Sadrah berdiri diam, membiarkan kata-katanya menggema di dalam pikiran. Wanita itu telah pergi, namun kehadirannya masih terasa. Kidung yang tadi terdengar pun kini mereda, namun jejaknya tertinggal di hati.
Langit yang tadi gelap perlahan mulai terang, meskipun matahari belum sepenuhnya terbit. Kabut yang tebal mulai menipis, memperlihatkan jalan di depan yang semakin jelas. Di kejauhan, Sadrah bisa melihat matahari perlahan-lahan muncul di cakrawala, mengusir kegelapan malam.
Sadrah menarik napas dalam-dalam, merasa lebih ringan. Ada ketenangan baru dalam dirinya, sebuah penerimaan akan peran yang harus ia jalani dalam dunia yang tak pernah berhenti berubah. Sadrah sadar bahwa meskipun hidup penuh dengan kekacauan, ada kekuatan yang lebih besar di luar sana yang selalu menjaga keseimbangan.
Dan dalam perjalanan ini, Sadrah tak sendirian. Ada alam, ada sejarah, ada warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, semua membentuk siapa manusia saat ini. Sadrah hanya perlu terus melangkah, sambil mendengarkan suara-suara yang mengiringi langkahnya, seperti kidung yang mengalun dalam kabut.
Pertanyaan Ketujuh – Hitam Dan Biru
“Pernahkah kau mengaku salah?”
Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan langit yang memudar ke warna jingga gelap. Sadrah berjalan sendirian di jalan yang sepi, diiringi angin dingin yang merayap di sela-sela pakaian. Perasaan sunyi dan gelisah kembali menghampiri, seperti bayangan yang tak pernah jauh dari langkah. Di depan Sadrah, dunia terlihat seperti panggung kosong, di mana segala yang pernah manusia pikirkan tentang benar dan salah mulai memudar, meninggalkan ruang hampa.
“Setiap manusia saling membawa pesan—berita yang tak menyenangkan, tentang sesama manusia, tentang dunia yang selalu penuh dengan pertanyaan. Setiap langkah seperti membawa beban yang lebih berat dari sebelumnya. Segala sesuatu yang terjadi selama ini, setiap luka dan penyangkalan, menggantung seperti bayangan yang siap menghantui kapan saja.”
Sadrah berhenti di tepi jalan, menatap sekeliling, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya tetap samar, seperti lukisan kabur yang sulit diartikan. Perasaan marah dan kecewa bercampur, membuat pikiran Sadrah semakin gelap. Di saat seperti ini, Sadrah sering bertanya-tanya, mengapa manusia terus berlari? Apa yang sebenarnya manusia hindari?
Dalam kesunyian ini, Sadrah ingin bicara. Tentang luka yang tak pernah mengering, tentang pikiran-pikiran yang begitu gelap. Ada banyak hal yang tersimpan dalam diri Sadrah. Hal-hal yang selama ini hanya ia tahan dan ia abaikan. Namun sekarang, Sadrah ingin berbagi, berharap ada yang mendengarkan, berharap ada yang mengerti.
Sadrah tahu, sadar dirinya kotor. Manusia membawa beban kesalahan masing-masing, berusaha untuk menerima, meski tak mudah. Dunia ini sering kali membuat manusia merasa lelah, membuat manusia lupa bahwa di balik semua ini, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar salah atau benar.
Suara angin yang berhembus membawa kilasan-kilasan memori. Wajah-wajah dari masa lalu muncul di pikiran Sadrah, mengingatkan pada semua yang telah terjadi. Sadrah melihat kawannya di sana, berdiri dengan mata penuh pertanyaan. Mereka berdua sama-sama tahu, hidup ini penuh dengan kesalahan. Namun, apakah mereka sebagai manusia pernah benar-benar mengakuinya? Atau manusia hanya terus berlari, berharap kesalahan-kesalahan itu akan hilang begitu saja?
“Berhenti sejenak,” bisik Sadrah pada diri sendiri. “Coba kita bicara.” Namun, semakin Sadrah mencoba untuk berbicara, semakin ia merasa sulit. Kata-kata seolah tertelan oleh kabut yang menyelimuti pikiran. Di dalam hati, Sadrah tahu bahwa semua—manusia, dunia—terlalu terperangkap dalam permainan salah dan benar, sehingga manusia lupa untuk menerima kenyataan yang ada.
Di tengah kebingungan ini, Sadrah menyadari bahwa ia hanya manusia biasa. Manusia yang berusaha untuk menerima dunia ini, meski itu sulit. Namun kadang, hanya dengan berhenti dan merenung, manusia bisa mulai menerima kesalahan-kesalahannya dan menyembuhkan luka-luka yang tersembunyi di balik senyum palsu masing-masing.
Dalam kontemplasi senja, Sadrah memandang dunia dengan mata baru, mencoba untuk menerima segalanya—baik dan buruk, salah dan benar—sebagai bagian dari perjalanan yang harus ia lalui.
Sadrah menatap langit yang mulai berubah menjadi hitam, menyatu dengan warna biru yang perlahan pudar. Dunia ini tidak sempurna, begitu pula manusia. Mungkin, di balik semua itu, ada sesuatu yang bisa manusia temukan. Sesuatu yang bisa membawa manusia lebih dekat pada kebenaran, meski itu tak pernah sepenuhnya jelas.
Sadrah menarik napas panjang, merasa lebih ringan meski perasaan itu belum sepenuhnya hilang. Namun, setidaknya sekarang, Sadrah merasa bisa menerima. Tentang dunia ini, tentang dirinya, tentang semua manusia.
Pertanyaan Kedelapan – Terbuang Dalam Waktu
“Apakah kau siap kehilangan?”
Kenangan tentang masa lalu kembali membayang, seperti asap tipis yang melayang di udara. Di tengah semua kebingungan ini, suaranya tiba-tiba muncul, memanggil Sadrah dari tempat yang jauh. Suara yang pernah begitu Sadrah kenal, begitu akrab, kini terasa seperti gema yang terputus dari waktu. Sadrah mengingat bagaimana dia dulu meyakinkan Sadrah bahwa mereka bisa melewati ini bersama. Namun sekarang, semuanya berbeda. Dewasa telah mengubah segalanya, mengubah cara mereka memandang dunia, mengubah cara mereka merasakan cinta dan kehilangan.
Sadrah merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ada masa lalu yang terus menarik kembali, membawa rasa sakit yang belum sembuh, luka-luka yang masih terasa perih. Di sisi lain, ada masa depan yang tak pasti, penuh dengan kabut dan kemarahan. Sadrah berusaha memahami semua ini, tapi semakin ia mencoba, semakin ia merasa tenggelam dalam ketidakpastian. Segala harapan yang pernah ia pikirkan, semua mimpi yang dulu ia bangun, kini terasa seperti berputar-putar tanpa arah.
Di dalam kabut itu, Sadrah melihat bayang-bayang ‘yang terdahulu’. Wajah ‘yang terdahulu’ dulu penuh tawa, kini tampak kabur. Dulu begitu dekat, namun seiring waktu, ada jarak membentang lebar. Sadrah tahu bahwa ‘yang terdahulu’ telah berubah. Harapan-harapan yang dulu dibangun bersama, kini tampak rapuh, seolah angin bisa meruntuhkannya kapan saja. Sadrah ingin kembali ke masa itu, masa di mana segalanya terasa lebih sederhana. Namun, seperti semua hal dalam hidup, waktu tidak akan pernah kembali.
Luka-luka yang pernah Sadrah tahan selama ini kini terkuak. Seperti pintu yang tiba-tiba terbuka, semua rasa sakit yang pernah ia tinggalkan di masa lalu tiba-tiba kembali, menyerbu tanpa peringatan. Tangis yang dulu ia tahan kini tak terbendung. Sadrah merasa seperti terjebak di dalam arus waktu, waktu yang terus berjalan tanpa peduli pada apa yang manusia rasakan, tanpa peduli pada harapan yang mungkin pernah manusia miliki.
Namun di balik semua ini, ada sesuatu yang tak pernah berubah. Cinta yang pernah dibagikan oleh ‘yang terdahulu’, masih ada di sana. Ketika Sadrah melihat ‘yang terdahulu’ dalam ingatan, Sadrah melihat tawa dan canda yang pernah menguatkan hati Sadrah. Sisa-sisa hari, sisa-sisa hidup, terasa lebih ringan karena Sadrah tahu bahwa cinta itu, meski telah berubah, masih tetap ada. Meski waktu terus berjalan dan memisahkan, Sadrah tahu bahwa cinta itu akan selalu menjaga, melindungi dari kebingungan dan ketidakpastian.
Sadrah duduk di tepi jurang waktu, merenungi perjalanan. Seiring pagi berganti dan waktu terus memeluk, Sadrah menyadari bahwa manusia akan tua, rentan dan sendiri, tapi itu tak apa. Senyum selalu memberi kekuatan untuk terus maju, meski jalannya tak selalu jelas. Cinta, pada akhirnya, tidak mengenal waktu. Cinta adalah satu-satunya yang abadi, yang akan terus menjaga, bahkan ketika semua hal lain mulai sirna dan kabur..
Dalam keheningan ini, Sadrah memutuskan untuk merangkul perasaan itu. Sadrah menerima bahwa hidup ini penuh dengan kehilangan, penuh dengan kesedihan. Namun di balik semua itu, selalu ada cinta yang tak pernah hilang, selalu ada harapan yang tetap menyala, meski kecil dan redup.
Jawaban – Manusia (Sumarah)
Kita semua adalah bagian dari siklus yang tak terhindarkan, siklus kehidupan yang terus berputar tanpa henti, seperti roda waktu yang menggilas segala hal yang berada di jalurnya. Pada akhirnya, kita hanyalah manusia, debu yang melayang di tengah semesta, terombang-ambing di antara takdir yang sudah dituliskan dan pilihan-pilihan yang kita buat dengan kesadaran terbatas.
Di malam yang sunyi, di atas batu karang, Sadrah duduk memandang bintang-bintang. Langit tampak tenang, bintang bersinar terang di atas kepala, seolah ingin memberi tahu bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Jauh di dalam hati, Sadrah tahu bahwa semua ini hanyalah sebuah ilusi. Kehidupan terus berputar, dunia akan terus berjalan, dengan atau tanpa manusia. Pertanyaannya adalah, apakah manusia siap menerima itu?
Sadrah teringat semua pertanyaan yang menghantui selama ini. Tentang makna dari hidup yang sementara, tentang dunia yang tak adil dan penuh dengan kebohongan, tentang kehilangan, kematian, dan kesendirian. Selama ini, Sadrah mencari jawaban di luar diri. Sadrah mencari jawaban di dunia, di manusia lain, di masa lalu dan masa depan. Namun pada akhirnya, semua jawaban itu tidak pernah benar-benar memuaskan. Seperti air yang mengalir, semua jawaban yang ia temukan selalu menghilang begitu saja, tak bisa digenggam.
Namun malam ini, dalam keheningan yang hanya diiringi gemerisik angin dan debur ombak, Sadrah sadar bahwa jawabannya bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar sana. Jawaban atas semua pertanyaan ini ada di dalam diri manusia sendiri. Manusia, pada akhirnya, harus mampu memaafkan manusia lain, memaafkan dunia yang tak sempurna ini, dan memaafkan diri mereka sendiri. Manusia harus bisa menerima bahwa ada hal-hal yang tak akan pernah bisa diubah, dan itu tak apa. Karena dalam penerimaan itu, manusia menemukan kedamaian.
Sadrah teringat saat-saat di mana ia merasa terbuang, saat di mana semua terasa hampa dan tak bermakna. Namun kini, Sadrah menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan ini. Semua manusia adalah pion-pion kecil dalam permainan kehidupan yang jauh lebih besar dari diri manusia itu sendiri. Dan dalam permainan ini, manusia tak bisa menang atau kalah, karena bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana manusia memainkan permainan ini, dengan hati yang terbuka, dengan kesadaran bahwa manusia tidak sendirian, dan dengan penerimaan bahwa manusia takkan pernah memahami semuanya.
“Langit semakin gelap, namun bintang-bintang tetap bersinar, seperti penanda bahwa meski malam datang, selalu ada cahaya di sana. Manusia mungkin hanya debu dalam semesta, tapi manusia adalah debu yang memiliki makna, yang memiliki perasaan, yang mampu menangis, tertawa, mencintai, dan merasakan. Dan di situlah letak keindahan hidup ini. Bukan pada apa yang manusia miliki, bukan pada apa yang manusia capai, tapi pada kemampuan manusia untuk merasakan, untuk memahami, dan akhirnya, untuk menerima.”
Seiring malam semakin larut, Sadrah merasa ringan, seolah beban yang selama ini ia tanggung perlahan-lahan menghilang. Semua kesalahan, semua penyesalan, semua rasa sakit, kini tampak kecil dibandingkan luasnya semesta ini. Sadrah sadar bahwa ia tidak sendiri. Semua manusia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Manusia adalah manusia, yang hidup dan berputar dalam siklus kehidupan dan kematian.
Sadrah memejamkan mata dan tersenyum, merangkul kenyataan bahwa hidup ini tak sempurna, dan tak perlu sempurna. Mungkin itulah yang selama ini ia cari. Bukan jawaban yang sempurna, tapi penerimaan bahwa jawaban itu tak pernah benar-benar ada. Bahwa yang paling penting adalah merangkul ketidaksempurnaan, memaafkan diri sendiri dan manusia lain, serta berserah pada takdir yang telah dituliskan untuk manusia.
“Jalaran Sadrah. Sumarah. Karena rela dan berserah diri. Bukan sebagai tanda menyerah, tapi sebagai tanda kedamaian. Karena dalam berserah, manusia menemukan kebebasan yang sebenarnya. Kebebasan untuk hidup, untuk mencintai, dan untuk akhirnya kembali ke tempat manusia berasal, dengan tenang dan damai.”
Editor: Arlingga Hari Nugroho
Foto sampul: Hu Shah Records