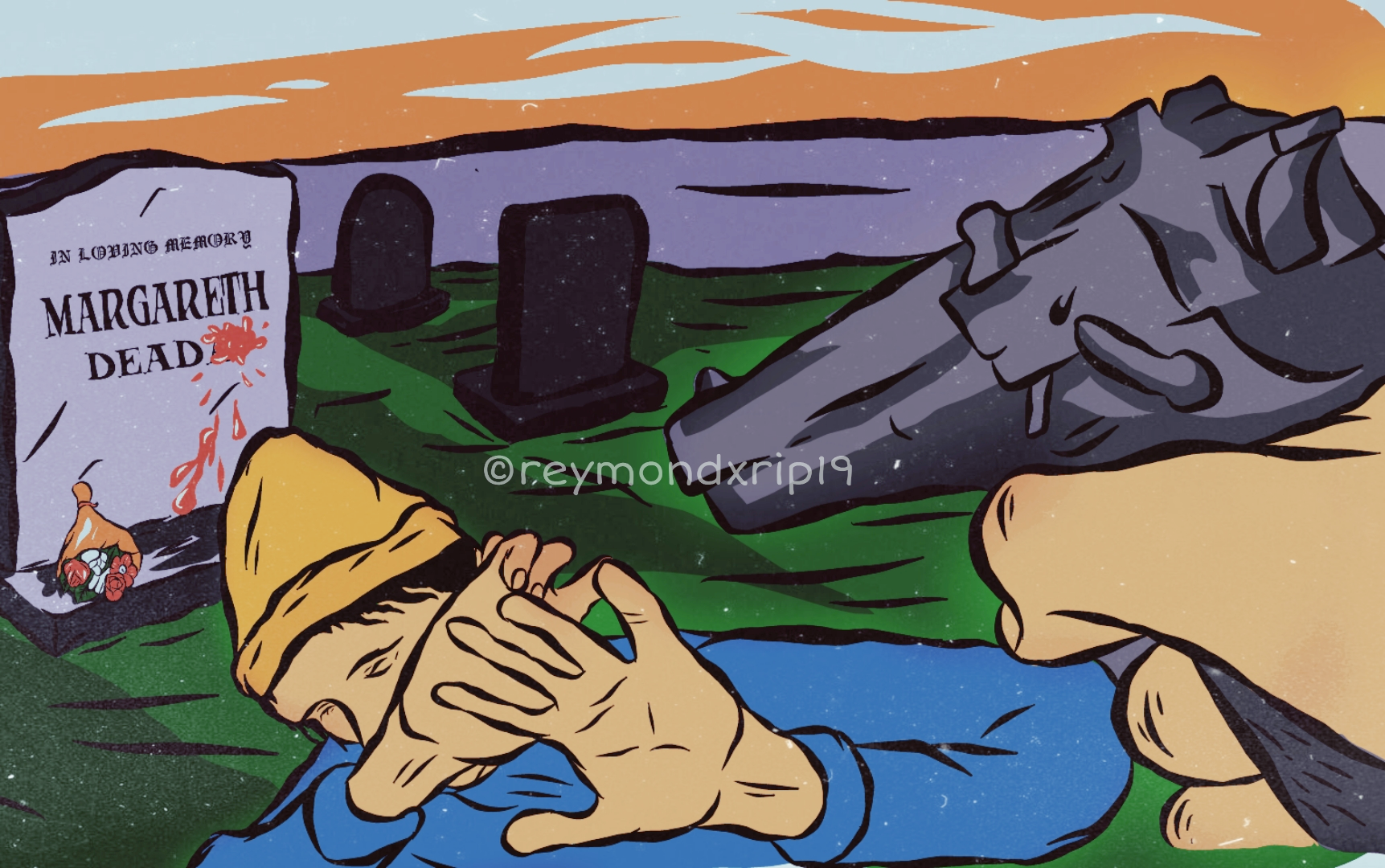Bangun pagi, sekitaran jam 07:05 WIB. Harusnya aku merapikan tempat tidur, kamar yang berantakan, gorong-gorong ranjang dan lemari yang di penuhi bangkai obat nyamuk dan nyamuknya, sarang laba-laba dan debu-debu. Setelah itu pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi. Dan membersihkan selat-selat berdaki yang ada di badanku.
Tapi hari ini terasa lain; merasakan dilema. Ada sedikit kekhawatiran yang entah dari celah mana ia menyelinap masuk ke pikiran. Pun semua kegiatan tadi, sampai detik terakhir beranjak dari tempat tidur; enggan dilakukan. Justru aku lebih memilih menyeduh kopi, kemudian menyalakan sebatang rokok, kemudian melamun lagi.
Di dalam kepala, rasanya hanya ada kebingungan-kebingungan yang menggumpal. Mungkin itu adalah sebuah dilema menghadapi semester mau tua ini. Mungkin juga wajar. Barangkali semua jenis mahasiswa dari jurusan apapun, juga demikian.
Seperti halnya aku yang bingung menyiapkan skripsi atau memilih tempat mau mengerjakan skripsi sebagai tugas akhir dimana; antara di rumah di Banten atau sekitar kampus di Bali; ambil penelitian di sana. Dua pilihan ini sulit untuk ditentukan dan tidak cukup dengan waktu satu hari merenungkannya. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain.
Semasa kuliah yang dirundung suasana virus sialan selama hampir dua tahunan, yang merambah ke aturan mesti belajar dengan work from home, menjadikan tubuh semakin kaku, pikiran beku, dan soal memilih sesuatu, pun bingungnya tujuh keliling. Aduh hyung… bingung, bingung, dan sangat bingung!
Hasrat untuk menelepon beberapa kawan dari bagian barat (Jawa) dan timur (NTT) bahkan spam chat dengan sengaja, tiba-tiba saja timbul, absurd.
“Mau skripsian dimana? Di Bali apa di rumah?” tanyaku pada mereka satu persatu dengan pertanyaan yang sama.
Jawabannya beragam. Sebagian ada yang memilih mengerjakan di sekitaran kampus dan di lingkungan tempatnya tinggal, tapi sebagian juga ada yang menjawab, “Belum dipikirkan!”.
Dan aku, masih tetap saja bingung. Tidak merasakan kepuasan atas jawaban mereka, karena mungkin itu adalah suatu pilihan hidup pribadi masing-masing orang yang sebenarnya setiap manusia mesti begitu; mesti memiliki pilihannya sendiri sebagai makhluk yang bebas.
“Mau dimana sisa-sisa semester ini dihabiskan?” Giliran aku bertanya kepada diri sendiri.
Rasanya, hati ingin di rumah. Kira-kira itu mungkin jawaban yang dikatakan tubuhku, yang sudah malas merantau jauh. Tapi, setelah melihat keadaan diri yang sudah bukan lagi kanak-kanak, seratus lima puluh kali aku harus berpikir berulang jika harus menyandarkan hidup terus berdiam diri di rumah.
Bisa-bisa habis dan bonyok jika lama-lama ada di rumah. Dirundung, dihina tak bernilai oleh tetangga, oleh orang-orang rumah karena terlihat menganggur dan tidak berguna selama dua tahun terakhir.
Jadi, yasudah. Mengalir saja mungkin, “Biarkan nasibku membuat penentuan atas dirinya sendiri di jalanan nanti. Lagi, menjadi penggelandang so’ intelek atau memang penggelandang aslinya!” kataku kepada segala macam kebingungan di kepala.
***
Bisa-bisanya ada sesuatu yang hampir aku lupa. Bahwa aku memiliki jadwal tetap, yang mestinya juga harus segera dikerjakan.
Sebenarnya tidak aku jadwalkan dengan sengaja sebagai kegiatan hidup yang terjadwal; menyapa perempuan yang sering duduk di kursi dan tersenyum paling senyap setiap kali aku tanya, “Sedang apa hari ini?”
Dia hanya membalas dengan kalimat yang tidak pernah berubah dan berganti setiap harinya dan selalu saja singkat seperti biasa. Walaupun demikian, aku merasa senang tiap kali menjawabnya.
“Memikirkanku?”
“Bukan! Aku sedang duduk di kursi. Seperti biasa.”
Dia adalah makhluk yang unik dan istimewa berjenis perempuan dari spesies manusia yang baru aku tahu selama dua puluh dua tahun hidup.
Keistimewaan yang ia punya, tentang dirinya yang tidak lagi menganggap sebuah perasaan sebagai cara hidup untuk mengolah hari. Terkecuali itu adalah sesuatu yang penting-penting.
Aktivitasnya hanya duduk di atas kursi menunggu hari berganti. Aku mulai membuat alasan bahwa, karena ini aku menaruh rasa paling dalam, seperti asmara. Dan aku ingin sekali seumur hidup, merasakan duduk bersama dengannya di kursi yang biasa ia duduki, sembari meminum kopi dan menyantap gorengan pisang atau pisang rebus untuk menikmati hari dengan hanya duduk-duduk saja, berdua.
“Kamu mau ngapain malam ini, Par?”
“Seperti biasa.”
“Memikirkanku?”
“Tidak! Duduk di kursi. Seperti biasa.”
Tapi malam itu, tidak dengan aktivitas yang sama aku perhatikan. Melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan di waktu pagi, ada perbedaan. Tidak lain adalah berdoa yang begitu khidmat, sehingga tidak kurusak suasananya; aku sepertinya perlu menunda. “Lain hari saja aku mampir ke rumahmu yah, Par. Ada urusan lain; meronda, tugas dari Pak RT 03/04.”
Ia berdoa tidak henti-henti, tubuhnya melengkung. Dari kejauhan kulihat kedua tangannya mengunci lututnya, sekaligus juga menengadah; layaknya seseorang meminta. Air matanya jatuh, satu tetes, dua tetes, sampai banyak tetesan-tetesan yang kemudian menyusul, semakin deras. Dan membasahi semua yang kejatuhan.
Sampai suara sedu-sedan, isak tangis mulai terdengar. Aku melihat dari kejauhan. Matanya juga adalah mata yang paling melankolis dan mengisyaratkan pesan untuk Tuhan; semoga, besok hari berbeda. Bewarna. Semoga, besok hari berbeda. Menyenangkan dan seterusnya dan seterusnya.
Aku teringat sebuah cerita yang pernah kudengar darinya. Par pernah cerita tentang alasan di balik ia memilih menikmati hari-harinya hanya di atas kursi tua di beranda rumahnya. Sebabnya adalah sebuah memori yang sudah dianggap menjadi bagian penting dari hidupnya.
Dahulu, ia punya sosok bapak sebelum menjadi lelaki yang meninggalkan kenangan pahit di ruang keluarga akibat sebuah tragedi perceraian, perselingkuhan. Lelaki itu pernah menikmati seperempat malam dengan Par di kursi itu dengan menyanyikan beberapa lagu kasih sayang seorang bapak pada putrinya; waktu Par berumur tujuh tahun.
Hanya ingatan itu yang ia punya. Dan dianggap paling indah untuk dinantikan lagi; kembalinya sesosok bapak dan lengkapnya formasi keluarga.
Sehingga sekarang ia masih mengabadikannya dengan menunggu keajaiban datang dari salah satu Tuhan yang ia yakini. Allah SWT.
Tidak persoalan itu saja, seperti halnya dalam dongeng-dongeng lawas tentang seorang gadis yang menunggu pangerannya datang untuk melepaskan sebuah kutukan hidup yang mengerikan; di cabik-cabik kesunyian.
Ia sesekali berdoa, menyematkan harapan kepada kemurahan Tuhan penuh, semoga seorang laki-laki datang sebagai pangerannya dan tidak meninggalkannya sebagai perempuan yang tidak berguna, seperti bapaknya kepada ibunya saat ini.
Hari mudah berganti, tapi aku masih dengan sikap yang tidak pernah berbeda atau berubah. “Kamu tidak ada jadwal menelvonku? Atau bertanya, aku lagi apa gitu, Par?” tanyaku lewat pesan singkat melalui WhatsApp; mencoba menghiburnya atas kesedihan malam kemarin.
“Hahaha… ngapain. Tidak penting!”
“Hehe… Yasudah. Mungkin lain waktu, semoga ada. Oiya, kamu lagi apa, Par?”
“Seperti biasa.”
“Memikirkanku?”
“Tidak! Seperti biasa, duduk di kursi.”
Percakapan selalu saja diawali dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang itu-itu saja. Dari banyaknya lelaki yang ia kenal, hanya aku yang datang dengan segala macam ketidakpentingan yang berarti, katanya. Tolok ukur seorang lelaki yang dipandangnya adalah yang berwibawa dan membawa topik obrolan yang penting-penting kepada seorang perempuan ketika berbincang.
Sedikit sedih sebenarnya mengetahui hal itu. Apalah daya aku yang sudah tenggelam dalam sapa dan cerita, ditambah menemukan senyumnya saja, seolah menjadi kutukan baru, karena sulit ditemukan walaupun hanya berbentuk simbol saja. Ia enggan memberiku dengan cuma-cuma, terkecuali aku membawakan sebuah topik yang dianggapnya penting.
Tidak sampai disana, aku berusaha meyakinkan, bahwa hidup yang tidak penting juga terkadang menyenangkan. Walaupun lebih banyak tidak jelasnya memang.
Hidup sebagai lelaki yang harus memenuhi segala macam tuntutan kejantanan. Sulit. Pergi dan menyapa seolah menjadi hal yang mesti dicurigai. “Laki-laki ini tidak berguna dan dia mencari sesuatu yang menghidupinya ke setiap perempuan yang berhasil ia sapa.” Selalu saja begitu, tatapan mendelik dan curiga dari orang-orang bertubuh maskulin dan feminin tulen.
Tubuhku tidak begitu lentur dan tak bergoyang saat di depan layar tujuh inci, aku seperti laki-laki pada umumnya padahal. Tapi mengapa hidup seorang lelaki mesti harus dipandang sama dengan laki-laki kebanyakan. Hidup seorang anak laki mesti serupa, melakukan keterampilan beserta caranya, juga harus serupa. Padahal itu tidak menyenangkan untuk dilakukan; hidup yang sama adalah hidup yang membosankan bagiku sendiri.
“Laki-laki itu ya terlahir begitu. Harus terlihat maskulin. Bisa manjat pohon, angkat galon. Gagah. Punya status sosial, minimal menjadi ketua umum di organ mahasiswa, kemudian bernilai di masyarakat dan memiliki pekerjaan yang layak setelah lulus nanti. Berani dan sedikit penting ketika berbicara dengan perempuan!” katanya.
“Tapi, apakah haram jika laki-laki juga ingin menyeimbangkan dirinya, menikmati hari-hari tanpa sesuatu yang normatif tadi, Par? Tidak bisa panjat pohon juga tidak apa-apa bukan? Tidak membawa sesuatu yang penting juga tidak akan merusak bumi bukan?”
“Iya… iya… iya… Dan tidak haram juga. Tapi, ya… aneh pasti. Masa iya, laki-laki nantinya menyuruh istrinya panjat pohon? Dan aku tidak ingin memiliki suami seperti itulah! Ditambah, jika dalam obrolannya terlalu membuang-buang waktu dan berkhayal, seperti kamu ini xixixxi….”
“Hmmmm… Iya, sudah. Barangkali memang harus begitu. Laki-laki selain dikutuk untuk maskulin tulen juga harus menguasai jurus monyet dan teori-teori komunikasi yang mutakhir.”
Ia tertawa. Suasana menjadi cair, meledak oleh tawanya. “Tapi tahukah kamu, Par? Bapakmu adalah lelaki yang aku benci, Par!”
“Apa urusanmu dengan bapakku?”
“Sebab, ia memiliki watak yang sama dengan laki-laki yang pernah menjadi kekasih ibuku. Sangat serius memperdaya ibuku agar hanya bergelut di dapur, tanpa kebebasan. Hampir mirip sebuah penjara yang tabu untuk disebutkan seperti itu. Merasa dirinya paling kuat, selir sana-sini ia tiduri tanpa memikirkan perasaan ibuku di rumah. Kemudian meninggalkan kami, menciptakan kenangan paling buruk setelah bercerai; terlantar!”
Pesanku yang aku kirim tidak ia balas. Aku pikir, mesti ada yang salah membalas demikian. Dan menaruh benci pada bapaknya juga, sepertinya kesalahan fatal.
“Par. Maaf perihal semalam. Dan Selamat pagi. Maaf, aku hampir lupa untuk tidak menyapa kamu dan meminta maaf. Ah, dasar aku. Hampir menjadi laki-laki pelupa.”
“Tidak apa-apa. Kita tidak memiliki kenangan juga. Selama kita kenalpun, barangkali adalah hanya sebuah hari yang kosong. Termasuk yang semalam!”
Setelah itu, Par tidak lagi bisa aku hubungi. Mungkin dia marah besar.
Entah bagaimana kabarnya sekarang. Selama 3 tahun tidak lagi berbincang, rasanya aku ingin bertemu sesekali dan menyapanya lagi walaupun hanya melalui ponsel, “Selamat pagi, Par”.
Tapi beberapa hari yang lalu, aku sudah kirim sebuah surat kaleng ke rumahnya, di kaleng beer yang aku ambil dari gorong-gorong ranjang kamarku. Setelah rampung, kutitipkan ke salah satu teman yang hendak melewati rumahnya. Di dalamnya terdapat tulisan tangan, aku buat dan kirim setelah aku baru mengetahui sesuatu tentang hidup terbarunya Par.
Dari seorang teman bahwa dirinya sudah keluar dari kursi dan beranjak bergabung dengan teman-teman perempuan di jalan kiri, bersama perempuan-perempuan yang melawan. Atau yang dikenal dengan gerakan feminis Marxis. Ia pergi untuk menggugat masa lalu ayahnya, perihal dosa-dosa yang pernah dilakukan kepada ibunya dan kepada dirinya.
Surat : Untuk Par.
Subjek : Tidak Penting.
Alamat : RT. 100/101
HARI PROTES
Kudengar.
Dari kejauhan, cerita terbaru hidupmu.
Membawaku kepelukan malam,
dekat dengan kursimu.
Surat kaleng ini aku kirim, atas itu.
Berceritalah, sampai kapan malam ini harus selalu gelap?
Dan kau bersembunyi dariku?
Perempuan, yang sempat duduk di atas kursi.
Perempuan, yang membenci harinya sendiri.
Dan yang sudah beranjak;.
Ke jalan kiri.
Menyuarakan sifat-sifat buas, laki-laki.
Dan mengutuknya!
Berceritalah, sampai kapan dunia ini tidak adil?
Dan kita masih belum bertemu, untuk menggugatnya bersama?
Aku ingin hari, bercerita penuh! Di pantai Anyer.
Tentang, aku punya sesuatu yang sedikit penting ;
Sesuai inginmu, dulu.
Yang tidak bisa ku tulis di surat ini, dengan bungkus kaleng bir. Apalagi.
Tapi.
Apapun, itu.
Semoga, harapanmu, bisa terwujud.
Semoga, ada perubahan ;
Yang lebih baik. Tentang perempuan yang melawan.
Perempuan, yang tidak lagi di atas kursi.
Perempuan, yang memegang botol api.
Hiduplah… Nyalalah..
Api sebuah protes!
Untuk selamanya!
Semoga kita bertemu, lagi;
Dimanapun.
Dan, “Selamat, pagi”.
Lain hari, semoga aku bisa menyapamu lagi. Dekat di bibirmu.
Serang, April 2022
Dedikasi untuk Nurul, semoga hari-harimu dipagari rahmat Tuhan
dan semoga selalu menyenangkan.